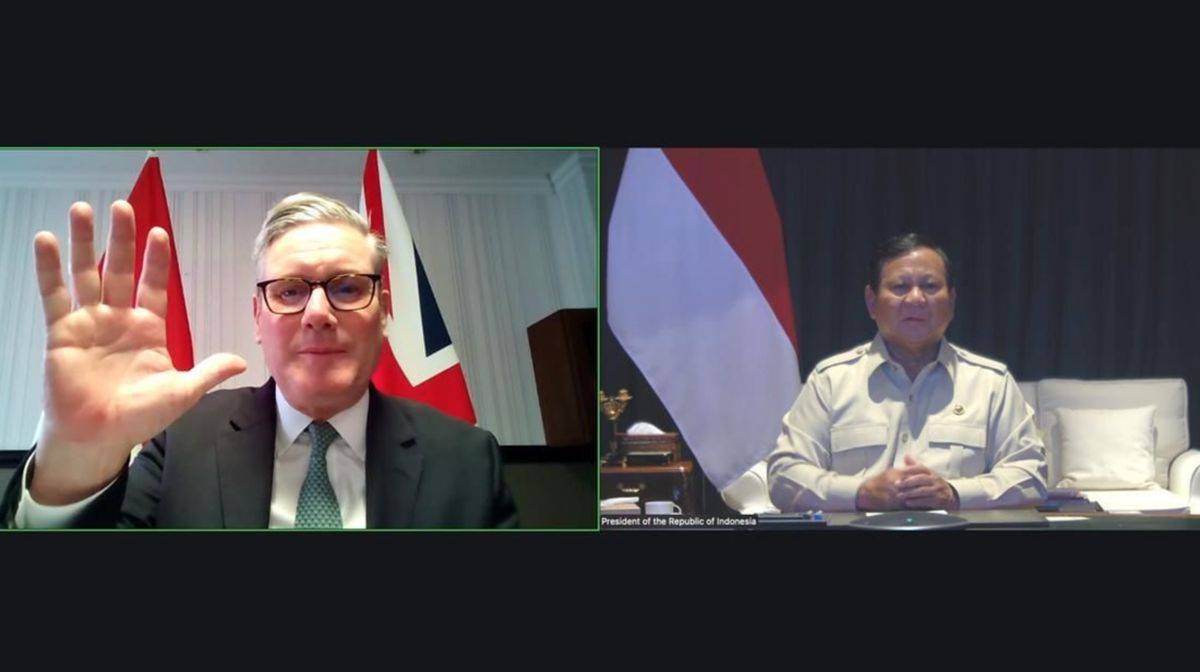Jakarta, CNN Indonesia --
Tujuh puluh delapan tahun setelah kemerdekaan, Pakistan masih berjuang keluar dari bayang-bayang kolonialisme.
Meski Imperium Britania resmi meninggalkan anak benua India pada 1947, struktur kekuasaan yang ditinggalkan tidak dihancurkan, melainkan diwarisi dan digunakan kembali oleh elite pascakolonial.
Birokrasi, militer, dan sistem hukum yang dulu dirancang untuk menundukkan penduduk India tetap dipertahankan oleh tuan tanah feodal, jenderal militer, dan birokrat, yang kemudian membentuk ulang hierarki kolonial demi kepentingan mereka sendiri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Alih-alih memperkuat integrasi nasional atau memberdayakan komunitas pinggiran, Pakistan justru memperdalam ketimpangan lewat sentralisasi kekuasaan yang ketat.
Bayangan kolonialisme internal itu paling nyata terlihat di Balochistan. Meski menjadi provinsi terbesar dan terkaya sumber daya alam, wilayah ini tetap miskin dan terpinggirkan secara politik.
Hasil tambang dan aset strategisnya dieksploitasi untuk keuntungan nasional, namun rakyatnya dibiarkan tertinggal. Proyek Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan (CPEC), yang digadang-gadang sebagai simbol kemajuan, justru memperlebar jurang ketidakadilan.
Warisan kolonial
Pelabuhan Gwadar lebih banyak mendatangkan tenaga kerja asing dan pasukan militer daripada peluang kerja bagi warga lokal. Bagi banyak orang Baloch, ini adalah bentuk baru perampasan tanah, hanya saja kini di bawah bendera Pakistan sendiri.
Dalam artikel "State discrimination and Balochistan insurgency" di Modern Diplomacy disebutkan bahwa meskipun kaya sumber daya, provinsi Balochistan hanya menerima sebagian kecil manfaat ekonomi, sementara sisanya dieksploitasi untuk negara pusat.
Nasib serupa dialami komunitas Pashtun dan Sindhi. Pashtun telah lama menjadi korban operasi militer dan penghilangan paksa, sementara gerakan nasionalis Sindhi terus diawasi dan ditekan. Dalam pandangan banyak kelompok minoritas, negara kini berperilaku seperti penjajah yang menindas perlawanan dan melemahkan identitas daerah demi mempertahankan kendali pusat.
Sistem hukum Pakistan juga masih mencerminkan warisan kolonial. Undang-undang peninggalan Inggris seperti Pasal 295A, yang dulu dipakai untuk mengontrol keberagaman India, kini digunakan untuk membungkam minoritas dan oposisi politik.
Di bawah rezim Jenderal Zia-ul-Haq, hukum-hukum tersebut diislamisasi lewat Ordonansi Hudud, yang semakin mempersempit kebebasan sipil. Di Balochistan, penghilangan paksa, pembunuhan di luar hukum, dan manipulasi pemilu menjadi potret aparat yang lebih mementingkan kontrol ketimbang keadilan.
Ketimpangan bahasa
Bahasa, yang seharusnya menjadi pilar identitas nasional, ikut menjadi alat penindasan. Setelah kemerdekaan, pemerintah memaksakan Urdu sebagai bahasa nasional tunggal, menyingkirkan bahasa daerah seperti Pashto, Sindhi, Balochi, dan Saraiki.
UNESCO mencatat bahwa penerapan Urdu sebagai bahasa instruksi di sekolah-sekolah Pakistan, meskipun hanya sedikit yang menggunakannya sebagai bahasa rumah, telah memperkuat ketegangan politik dan identitas.
Ketimpangan ini mencapai puncaknya ketika bahasa Bengali, yang digunakan oleh mayoritas penduduk Pakistan Timur, ditolak status resminya. Penindasan linguistik itu memicu Gerakan Bahasa 1952, yang akhirnya berkontribusi pada perpecahan dan lahirnya Bangladesh pada 1971-sebuah peringatan bahwa penyeragaman identitas justru bisa menghancurkan persatuan.
Studi akademis "Language-Based Nationalism: A Historical Analysis of Bengali Language Movement 1952" membahas bagaimana kebijakan bahasa pascakolonial Pakistan mengabaikan bahasa daerah, khususnya Bengali, yang kemudian memicu fragmentasi nasional.
Kini, hierarki bahasa di Pakistan tampak jelas: bahasa Inggris menjadi simbol status dan kekuasaan; Urdu menempati lapisan menengah; sementara bahasa daerah tersingkir dari ruang publik dan pendidikan. Kebijakan ini bukan sekadar administratif, melainkan bentuk kolonialisasi budaya yang menghapus narasi lokal dari wacana nasional.
Lingkaran kekuasaan lama
Ketimpangan serupa terlihat di wilayah 'Azad' Jammu dan Kashmir, di mana protes baru-baru ini menunjukkan perlakuan pemerintah pusat terhadap daerah pinggiran sebagai wilayah bawahan. Warga menuntut keadilan, royalti sumber daya, dan hak politik yang lebih besar-tuntutan yang justru dibalas dengan represi dan pengerahan pasukan.
Bahkan Perdana Menteri Shehbaz Sharif sempat mengakui bahwa Pakistan menghadapi "masalah elite," di mana segelintir kalangan militer, feodal, dan pengusaha besar mendominasi politik serta ekonomi negara sambil memberi sedikit manfaat bagi rakyat.
Perilaku elite militer mencerminkan pola penguasa kolonial: memusatkan kekuasaan, mengeruk kekayaan, dan hidup terpisah dari masyarakat. Melalui lembaga seperti Fauji Foundation dan Army Welfare Trust, mereka membangun kerajaan bisnis raksasa yang lebih berorientasi pada keuntungan daripada pengabdian publik.
Sementara itu, banyak keluarga pejabat tinggi militer memilih menetap di luar negeri-sebuah simbol mentalitas kolonial baru: menikmati kenyamanan di negeri asing sambil meninggalkan rakyat di tengah ketidakstabilan.
Tujuh dekade setelah kemerdekaan, Pakistan masih terjebak dalam lingkaran kekuasaan lama: sistem yang diwarisi dari penjajah, dijaga oleh elite, dan dijalankan atas nama persatuan nasional. Kolonialisme mungkin telah berakhir di atas kertas, tetapi bagi banyak warga pinggiran Pakistan, kemerdekaan sejati masih terasa jauh dari jangkauan.

 1 month ago
15
1 month ago
15