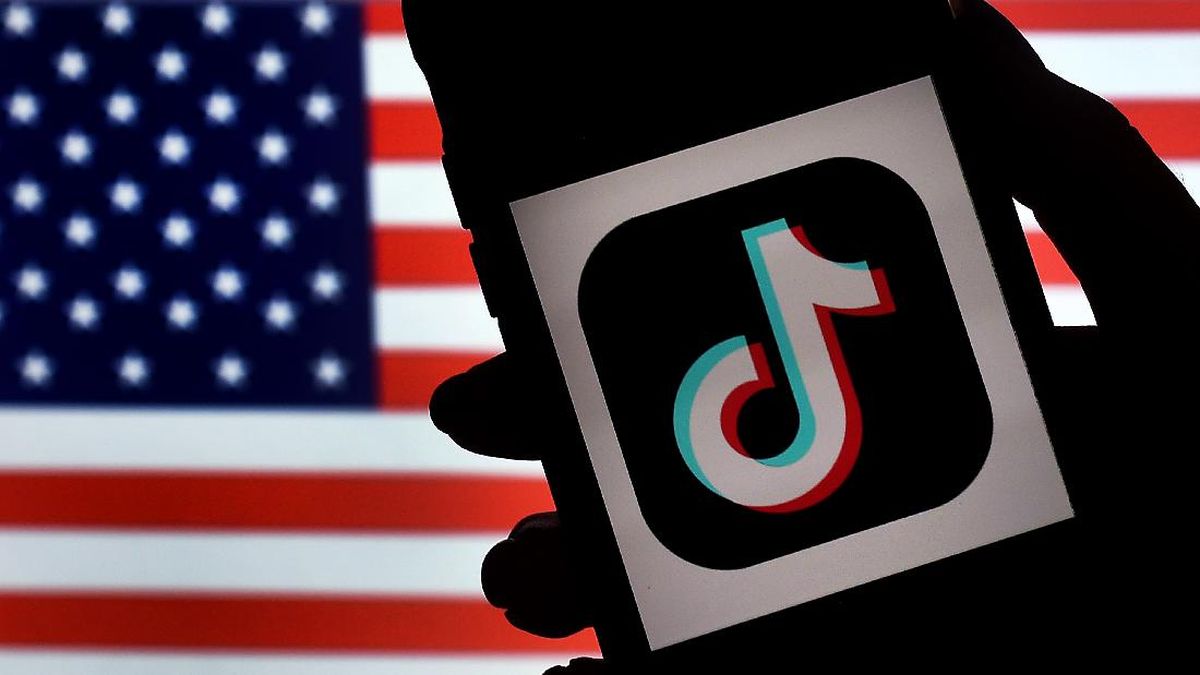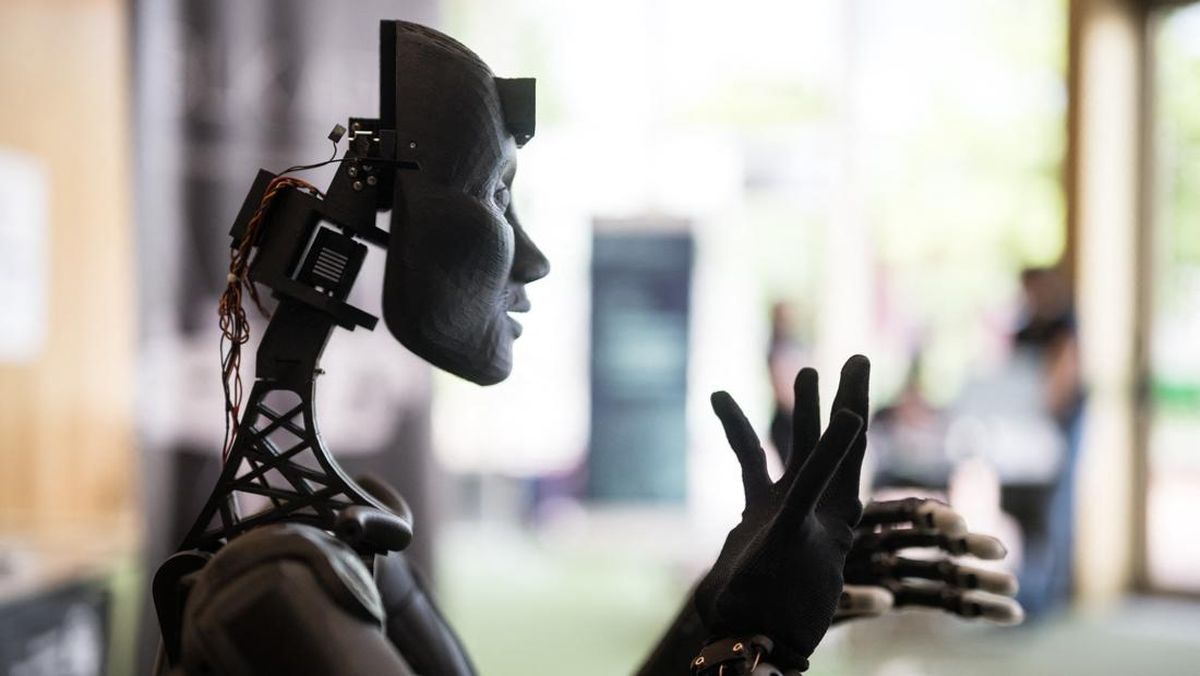Jakarta, CNN Indonesia --
Teknologi kecerdasan buatan (AI) kian berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Terlebih dengan kehadiran AI generatif atau Gen AI yang semakin mudah untuk diakses.
'Ledakan' kecerdasan artifisial ini pun tak lepas dari sorotan. Ada yang menyambut positif, dan tidak sedikit juga yang khawatir dengan keberadaan AI.
Pasalnya, keberadaan AI dikhawatirkan bakal menggantikan peran manusia. Di sisi lain, penggunaan AI terlalu berlebihan juga bisa berimbas buruk.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sawitri, Country head marketing JobStreet Indonesia, mengungkap penggunaan berlebihan pada AI dapat membuat pekerja malas sampai "membuat kita berhenti berpikir". Meskipun dapat digunakan untuk berdiskusi mencari ide, AI ternyata dapat menumpulkan ide jika digunakan secara berlebihan.
"Dan ide semuanya pakai AI, lama-lama ide kita tumpul. Kita enggak tahu mana yang bagus, mana yang enggak, pokoknya semua dari AI bagus. Nah itu yang sangat disayangkan," jelas Sawitri dalam acara Peluncuran Laporan Eksklusif terbaru Decoding Global Talent 2024: GenAI Edition di kantor JobStreet Jakarta, Selasa (29/10).
JobStreet, dalam laporan hasil survei bertajuk 'Decoding Global Talent 2024' GenAI Edition, mengungkap bagaimana pekerja di Indonesia terlalu bergantung dengan AI generatif.
Survei Jobstreet dilakukan terhadap 19.154 responden dari pekerja di berbagai industri, mulai dari IT hingga layanan kesehatan.
Hasil survei menunjukkan 10 persen responden Indonesia menggunakan AI secara mentah-mentah tanpa diperiksa ulang. Lalu 49 persen responden mengambil hasil AI dan dikoreksi ulang sebelum digunakan.
Hanya 28 persen responden yang menggunakan AI sebagai awalan dan sisanya dikerjakan secara mandiri.
"Hampir setengah dari responden Indonesia meninjau dan memodifikasi hasil GenAI (salah satu bentuk AI), menunjukkan kepercayaan dan ketergantungan yang lebih tinggi pada AI," demikian keterangan JobStreet, Selasa (29/10).
Sementara itu, sektor pekerjaan yang paling sering menggunakan AI adalah pekerjaan-pekerjaan yang berbasis teknologi seperti data science, IT, dan yang berhubungan dengan digital.
Dalam hasil survei, 78 persen responden berpikir bahwa AI akan mengubah beberapa aspek pekerjaan mereka. Lalu 40 persen memperkirakan dampak besar yang dapat menghilangkan atau mengubah pekerjaan mereka.
"Kekhawatiran ini paling tinggi di kalangan profesional dalam digitalisasi, ilmu data, dan AI, dengan 47 persen memperkirakan perubahan besar pada peran mereka." tulisnya.
Bikin burnout
Ketika ChatGPT mulai populer akhir 2022, Anurag Garg, pendiri agensi Everest PR mendorong timnya yang terdiri dari 11 orang untuk mengintegrasikan teknologi ini dalam alur kerja untuk kebutuhan persaingan dengan kompetitor.
Garg meminta karyawannya memanfaatkan AI untuk mengembangkan ide cerita hingga membuat catatan rapat.
Alih-alih meningkatkan produktivitas, teknologi ini justru membuat para karyawan burnout. Para karyawan merasa beban kerja meningkat karena harus membuat prompt, cek ulang hasil AI yang sering tidak akurat, dan terus beradaptasi dengan pembaruan fitu.
"Terlalu banyak gangguan. Tim mengeluh bahwa tugas mereka memakan waktu dua kali lebih lama karena kami sekarang mengharapkan mereka menggunakan alat AI," ucap Garg, melansir BBC, Rabu (30/10).
Selain itu, Garg merasa kewalahan dengan lonjakan alat AI baru yang terus dirilis. Sambil menggunakan ChatGPT, ia juga harus menggunakan Zapier untuk mengawasi tugas tim dan Perplexity untuk riset klien.
"Saya terus-menerus perlu mengawasi beberapa alat AI untuk menjalankan tugas, yang menjadi semakin rumit. Sulit untuk melacak alat mana yang seharusnya melakukan apa, dan saya mulai merasa sangat frustrasi," tambahnya.
Menurut survei Upwork terhadap 2.500 pekerja di AS, Inggris, Australia, dan Kanada, meskipun 96 persen eksekutif mengharapkan produktivitas meningkat dengan AI, 77 persen pekerja merasa beban kerja bertambah.
Studi oleh Resume Now juga menunjukkan 61 persen responden khawatir penggunaan AI akan meningkatkan risiko burnout, terutama bagi mereka di bawah usia 25 tahun.
"Menggunakan beberapa aplikasi membutuhkan waktu tambahan untuk mempelajarinya dan beralih di antara aplikasi-aplikasi tersebut, dan waktu yang hilang ini menyakitkan karena kita sangat sensitif terhadap waktu yang terbuang," tutur Cassie Holmes, profesor manajemen di Universitas California Los Angeles.
(wnu/dmi)

 2 months ago
27
2 months ago
27